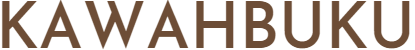Krakatau: Syair Lampung Karam 24 December 2018 – Posted in: Book Excerpts
Pada Agustus 1883 letusan besar gunung berapi meluluhlantakkan dua per tiga Pulau Krakatau yang terletak di Selat Sunda, di antara Sumatra dan Jawa. Tsunami memorakporandakan wilayah itu, dan guncangannya terasa di seluruh dunia. Sumber resmi menyatakan korban tewas 36,417 jiwa, tetapi beberapa sumber lain memperkirakan jumlah sebenarnya tiga kali lipat; diyakini hampir 120,000 orang menemui ajalnya. Abu letusan itu memengaruhi pola cuaca global hingga bertahun-tahun.
Gunung berapi lebih kecil yang dinamai Anak Krakatau muncul pada tahun 1928, masih aktif hingga sekarang. Satu-satunya laporan saksi mata pribumi yang tersisa tentang peristiwa tersebut — Syair Lampung Karam, oleh Muhammad Saleh — disajikan pertama kalinya di sini dalam terjemahan bahasa Inggris, The Tale of Lampung Submerged.
Saleh, seorang penduduk Lampung, menulis kisahnya dalam bentuk syair, salah satu bentuk puisi lama Melayu. Syair adalah genre sastra Melayu yang dipakai untuk berbagai tujuan, termasuk pengajaran agama dan penyebaran berita. Syair naratif panjang ini menceritakan reaksi warga setempat terhadap malapetaka yang menimpa seluruh wilayah itu dan memperkaya pengetahuan kita tentang bencana alam Krakatau ini.
Pulau gunung berapi Krakatau memiliki sejarah geologi yang panjang dan rumit. Dulu terdapat gunung berapi purba yang tingginya diperkirakan 200 meter. Gunung itu meletus dan hancur, menyisakan tiga pecahan besar: Pulau Sertung, Pulau Rakam, dan Pulau Rakata Kecil. Rakata mulai ditutupi lapisan lahar dari gunung berapi basal, membesar hingga mencapai tinggi 800 meter. Dua gunung berapi lain, Gunung Danan dan Gunung Perbuatan muncul dari dasar laut dan menyatu dengan Rakata, membentuk Pulau Rakata pra-1883. Sebelum letusan 1883, aktivitas besar terakhir pusat-pusat gunung berapi ini tercatat pada periode 1680-81. Keberadaan fumarol, atau lubang gas, sudah dilaporkan sejak 1839.
Awal 1883 tercatat adanya peningkatan signifikan aktivitas gempa bumi di wilayah itu. Pada 20 Mei letusan gunung berapi dimulai, pertama dari kawah Gunung Perbuatan dan beberapa hari kemudian dari lubang lain yang baru terbentuk. Bulan Juli kekuatan letusan meningkat, pertengahan Agustus sudah ada tiga lubang besar dan banyak lubang kecil yang menyemburkan abu dan uap air dalam jumlah besar.
Aktivitas tiga hari terakhir — 26, 27, dan 28 Agustus — ditandai oleh ledakan dahsyat beruntun, mula-mula berselang sepuluh menit, lalu sambung-menyambung. Batu apung dan abu dimuntahkan berlimpah-limpah bersama bongkahan batu. Tanggal 27 Agustus, tiga bulan lebih setelah aktivitas gempa pertama Rakata, pukul 05.30, 06.44, 10.02, dan 10.52, ledakan besar menandakan runtuhnya kawah Gunung Danan, kawah Gunung Perbuatan, dan bagian barat laut kawah Gunung Rakata.
Abu membubung hingga setinggi tujuh puluh kilometer, dan tsunami yang menyertainya menyapu tepian Selat Sunda, dengan ombak setinggi empat puluh meter di pantai. Gelombang itu mencapai Australia dalam waktu lima jam, Sri Lanka enam jam, Kalkutta sembilan jam, Aden dua belas jam, Cape Town tiga belas jam, dan demikian dahsyatnya sehingga masih terasa di Cape Horn tujuh belas jam kemudian. Kaldera yang terbentuk akibat ledakan itu bergaris tengah 5-7 kilometer dengan kedalaman 279 meter di bawah permukaan laut. Kawah itu berubah sejak kemunculan gunung berapi Anak Krakatau di pinggir timur laut kawah utama.
Dampak letusan itu tidak hanya dirasakan di Indonesia dan tetangga dekatnya; abunya masuk ke atmosfer dan mendinginkan iklim global sampai bertahun-tahun. Krakatoa Committee of the Royal Society of London menerbitkan laporan lengkap pada tahun 1888, berjudul The Eruption of Krakatoa and Subsequent Phenomena. Sejak itu Krakatau menjadi topik dalam banyak laporan dan terbitan, baik di bidang akademis maupun sastra. Sekarang pun masih menjadi topik penelitian yang penting. Krakatau: A Selected Natural History Bibliography, terbit 1982, mencantumkan tidak kurang dari 1,083 rujukan tentang letusan itu dalam beraneka ragam bidang, di antaranya geologi, zoologi, botani, meteorologi, dan oseanografi. Beberapa judul yang terbit kemudian — seperti Krakatau: The Day the World Exploded: August 27, 1883 karya hebat Simon Winchester, terbit 2003 — menandakan bahwa minat masyarakat pada Krakatau masih sangat besar.
Syair Lampung Karam terbit tahun 1883, disusul tiga edisi berikutnya yang dikeluarkan dalam kurun lima tahun. Namun, naskah tersebut terlupakan orang, mungkin karena ditulis dengan aksara Jawi sehingga hanya dipahami oleh kalangan yang berminat pada sastra Melayu klasik dan mampu membaca aksara Jawi.
Syair Lampung Karam terbit dalam empat edisi litografi antara 1883 dan 1888, dengan empat judul yang berbeda-beda sedikit, diterbitkan di Singapura. Edisi pertama syair ini panjangnya 42 halaman dan berjudul Syair Negeri Lampung yang Dinaiki oleh Air dan Hujan Abu. Kolofonnya menyatakan bahwa edisi ini diterbitkan pada tahun 1301 H (November 1883 hingga Oktober 1884). Satu eksemplar buku kecil ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, satu eksemplar lagi di Perpustakaan Negara Rusia, Moskwa.
Edisi kedua, yang berjudul Inilah Syair Lampung Dinaiki Air Laut, diterbitkan di Singapura pada tanggal 2 Safar 1302 H Perpustakaan Nasional di Jakarta.
Edisi ketiga, yang berjudul Syair Lampung dan Anyer dan Tanjung Karang Naik Air Laut, diterbitkan pada tanggal 27 Rabiulawal 1303 H (3 Januari 1886). Nama penerbitnya Haji Said. Dalam beberapa iklan buku ini, judulnya adalah Syair Negeri Anyer Tenggelam. (Anyer adalah kota di pesisir barat laut jawa, yang dipisahkan Selat Sunda dari Lampung). Satu eksemplar edisi ini tersimpan di Cambridge University Library.
Edisi terakhir yang diketahui, yang mendasari alih aksara dan terjemahan syair yang dimuat dalam buku ini, berjudul Inilah Syair Lampung Karam Adanya . Edisi ini diterbitkan pada tanggal 10 Safar 1306 H (16 Oktober 1888). Buku ini tersimpan di Perpustakaan Nasional di Jakarta; Leiden University Library; School of Oriental and African Studies, University of London; Perpustakaan Universiti Malaya; dan koleksi buku berbahasa Melayu milik misionaris Metodis Emil Lüring di Frankfurt.
Kolofon edisi pertama maupun keempat mengungkapkan bahwa syair ini digubah oleh Muhammad Saleh (lihat bait 374: “Hamba mengarang fakir yang hina / Muhammad Saleh nama sempurna”) di Kampung Bangkahulu (sekarang Jalan Bencoolen) di Singapura (lihat bait 369: “Di Singapura duduk mengarang / Di Kampung Bangkahulu disebut orang”).
Dalam syair ini juga (lihat bait 4: ” Awal mula hamba berpikir / Di Tanjung Karang tempat musyafir”), penulis menyatakan bahwa dia datang dari Tanjung Karang dan bahwa dia menyaksikan malapetaka yang disebabkan oleh letusan dahsyat itu (lihat bait 103: “Bermacam riwayat hambar sebutkan / Bertemu mayat di tepi lautan / Tiadalah sah tampak kelihatan / Hamba memandang bagaikan pingsan”). Tidak banyak yang diketahui tentang penulis; dia mungkin salah seorang pengungsi yang menyelamatkan diri ke Singapura, membawa kenangan pahit tentang bencana itu. Sayangnya, dia tidak menyebutkan tempat kelahirannya. Di Lampung ada cerita tentang tokoh yang agak legendaris bernama Muhammad Saleh (atau Soleh), ulama yang berperan penting dalam pembangunan Mesjid Jamik al-Anwar di Teluk Betung, Lampung, yang dimulai tahun 1839. (Mesjid itu hancur akibat letusan Krakatau tahun 1883, lalu dibangun lagi di kemudian hari.)
Muhammad Saleh berasal dari Bone, Sulawesi Selatan Dengan pengetahuan agamanya yang luas, dia menjadi penghulu terpandang di Teluk Betung dan kemudian diangkat menjadi bupati. Dalam artikel yang dimuat di Lampung Post tahun 2010, wartawan Zulkarnain Zubairi dan Iyar Jarkasih mengemukakan kemungkinan bahwa Muhammad Saleh yang disebut dalam kolofon pada syair edisi 1888 sama dengan ulama tersebut, tetapi tidak ditemukan bukti tertulis yang mendukung klaim ini.
Pada dua bait terakhir dalam syair, penulis menyebut “hati gundah gulana,” dan betapa sulitnya dia melupakan bencana itu; “Allah dan Rasul yang mengetahuinya / Hati di dalam sangat siksanya.” Begitu gundahnya si penulis, sehingga dia cemas bahwa ajalnya akan segera tiba: “Terlalu banyak pikir kiranya / Terkena demam hampir matinya.” Dalam banyak bait syair, dia menyatakan bahwa dia menyaksikan dampak letusan itu dengan kedua matanya sendiri. Mengutip dua contoh saja, dalam bait 84 dia menulis, “Demikian, Tuan, khabarnya orang / Hamba memandang nyatalah terang,” dan dalam bait 103, “Hamba memandang bagaikan pingsan.” Meski demikian, karena tidak ada informasi biografi tentang penyair, kita tidak mungkin dapat membuktikan klaimnya bahwa dia merupakan saksi mata langsung.
Penyair menyebut dalam bait 12, “Tahun 1300 pada Nabi kita / Kekasih Allah, Tuhan semata / Pada bulan Syawal pula dikata / Hari 22 sudahlah nyata” dan bait 13, “Hari Ahad nyatalah tentu / Pukul empat jam di situ / Berbunyi guruh menderu-deru / Dikatakan kapal apinya itu” bahwa pada pukul empat subuh pada hari Ahad, 22 Syawal 1300 H (26 Agustus 1883) dia mendengar suara gelegar dari laut, yang dikiranya suara peluit kapal api. Sebenarnya, suara itu menandakan letusan besar pertama Krakatau, yang dimulai satu setengah jam kemudian, pada pukul 5.30.
Penerbit edisi 1888 adalah Cap al-Hajj Muhammad Tayib (atau Taib). Dari kolofon bukunya, kita tahu bahwa Encik Ibrahim, penyalin edisi 1884, juga menjadi penyalin edisi 1888. Encik Ibrahim adalah juru tulis Melayu yang produktif, tinggal di Riau sebelum pindah ke Singapura, lalu pada tahun 1881 mulai bekerja di percetakan litografi setempat. Dalam kurun waktu enam tahun dia menyalin dua belas naskah untuk Muhammad Tayib dan puluhan percetakan lain. Seperti yang disebutkan Ian Proudfoot dalam Early Malay Printed Books, selama hampir dua puluh tahun “Ibrahim menjadi penyalin litografi terkemuka di Singapura, bekerja sama dengan sebagian besar percetakan litografi yang aktif pada masa itu.”
Dalam bait 367, “Tamatlah syair berhati gundah / Kepada Hijrah Nabi yang indah / Seribu tiga ratus bilangan sudah / Mendapat bahala negeri syahadah” dan bait 368, “Tahun Rabi ketikanya itu / Sehari Zulhijjah bilangan tentu / Empat belas hari rasanya itu / Hari Isnin pukulnya satu” pada edisi 1888, Muhammad Saleh menyatakan bahwa dia selesai menulis syair itu pada hari Senin, 14 Zulhijjah 1300 H (15 Oktober 1883) — hanya dua bulan setelah Krakatau meletus. Menimbang bahwa edisi litografi pertama syair ini muncul di Singapura segera setelah itu, mungkin saja si penulis diminta menuliskan ceritanya oleh orang yang memiliki koneksi dengan penerbit di Singapura, bahkan mungkin oleh Encik Ibrahim sang penyalin-penerbit itu sendiri.
Ian Proudfoot menjelaskan lebih lanjut bahwa pada akhir abad kesembilan belas percetakan pribumi dan Tionghoa peranakan di Singapura bersaing ketat. Karena Syair Lampung Karam memuat informasi mendalam dari saksi mata tentang letusan dahsyat yang baru terjadi di Hindia Belanda yang bertetangga, syair ini mungkin diperebutkan oleh para penerbit di Singapura. Rupanya edisi pertama buku itu memang laris, karena edisi kedua diluncurkan pada akhir 1884, tak sampai setahun setelah penerbitan edisi pertama.
Syair Lampung Karam dapat digolongkan sebagai “syair kewartawanan”, meminjam istilah yang digunakan oleh pakar bahasa Melayu klasik, Sri Wulan Rudjiati Mulyadi. Jenis syair ini biasanya mengandung laporan saksi mata tentang peristiwa nyata, termasuk peristiwa bersejarah dan perkembangan politik, selain bencana alam. Namun, dalam syair ini penyair lebih ingin bercerita tentang bencana alam yang dialaminya, daripada mengeksploitasinya.
Dalam syair aslinya, dengan 375 bait empat-baris, Muhammad Saleh menceritakan malapetaka yang ierjadi setelah Krakatau meletus. Dia menggambarkan dengan terperinci nasib banyak kota dan desa di wilayah Sumatra bagian selatan, yang puluhan ribu penduduknya tewas akibat bencana itu. Dia memaparkan bagaimana, meski menghadapi musibah sebesar itu, orang masih saling menolong. Dia pun bercerita dengan gamblang tentang orang yang mengail di air keruh, mencuri harta benda orang lain. Sebagai seorang Muslim, dan sesuai dengan selera zaman itu, dia menuliskan hikmah dan nasihat, menyiratkan bahwa saat menghadapi bencana alam sebesar letusan Krakatau, orang menjadi semakin bertakwa dan mengingat Allah Mahakuasa.
Mungkin ini generalisasi, tetapi di Indonesia, negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, orang cenderung memandang bencana alam sebagai peringatan atau hukuman dari Tuhan. jadi, misalnya, korban selamat gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada bulan Desember 2004 mengungkapkan perasaan mereka dalam kerangka spiritual.
Dalam tesisnya “Muslim Theological Perspectives on Natural Disasters,” Reza Indria melaporkan bahwa kegiatan agama di tengah korban bencana meningkat jauh. Banyak politikus dan pemuka agama juga menyebut kemerosotan moral bangsa sebagai penyebab berbagai bencana alam yang menimpa Indonesia selama dasawarsa terakhir. Mereka berkata bahwa bencana alam akan terus berlanjut, kecuali jika bangsa Indonesia berupaya memberantas korupsi dan pornografi, serta menjauhi gaya hidup konsumtif dan hedonis.
Di Indonesia, pandangan masyarakat tentang bencana alam dipengaruhi oleh sudut pandang agama maupun kepercayaan tradisional. Jika pemikiran Muhammad Saleh dianggap mewakili keyakinan masyarakat umum pada akhir abad kesembilan belas, ini berarti pandangan seperti itu rupanya sudah lama berada dalam benak masyarakat Nusantara, dan kemungkinan akan diwariskan kepada generasi mendatang.
Sumber Petikan
“Pendahuluan.” Introduction. Trans. Femmy Syahrani. Krakatau: The Tale of Lampung Submerged. Trans. John H. McGlynn and Suryadi. By Muhammad Saleh. 1st ed. Singapore: NUS Press, 2014. Print.