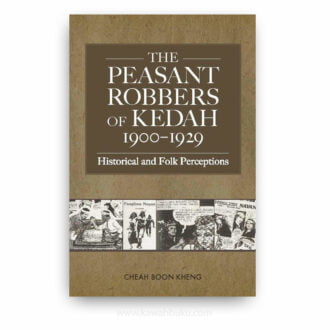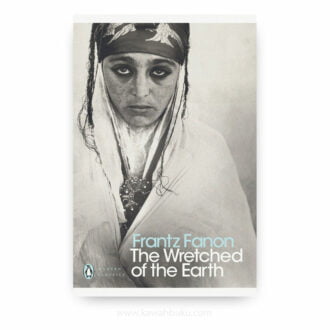Mengulangbaca Cheah Boon Kheng Menjelang Kemerdekaan
Membaca semula makalah Cheah Boon Kheng berjudul “Decolonising History: The Post-Modernist Challenge”1, pastinya sebagai sebuah refleksi kemerdekaan yang akan kita raikan, mengulangingat bahawa usaha dekolonialisasi sejarah sebenarnya bukanlah semata soal akademik, tetapi sebuah pertarungan epistemologi yang panjang. Ia bukan hanya tentang apa yang kita tulis pada masa lalu, tetapi bagaimana cara kita menulis dan dari sudut pandang yang bagaimana kita melihatnya.
Makalah ini tidak berhenti hanya pada sekadar kritikan terhadap sejarah kolonial, sebaliknya ia meracik persoalan yang lebih halus iaitu apakah kita benar-benar bebas daripada kerangka epistemologi Barat yang telah kita warisi? Persoalan ini benar-benar menggugah jiwa dan akal merdeka samada kita benar bebas atau terus hidup dalam bayang-bayang penjajahan.
Cheah Boon Kheng dalam makalah tersebut memulakan perbincangan dengan mengimbau kembali perdebatan tahun 1960-an, satu era tatkala negara-negara dunia ketiga baru beroleh kemerdekaan. Pada ketika ini mereka rancak membina naratif sejarah kebangsaan mereka sendiri. Sejarawan nasionalis ketika ini juga berusaha mengangkat kembali suara dan peranan masyarakat yang sebelum ini ditenggelamlemaskan dalam historiografi kolonial.
Kata Cheah, “The aim was not to obliterate the European colonialist entirely from their historical accounts, but to portray all anti-imperialist struggles as steps leading towards a sovereign national state.”2 Nyatanya pada era tersebut sejarah ditulis untuk menegaskan perihal kewujudan bangsa, menandai perjuangan antiimperialisme, dan menuntut kedaulatan politik. Ia membawa kita kepada persoalan yang lain, adakah cukup dengan perihal sebegini untuk kita menyahjajah sejarah? Atau sebenarnya kita hanya sedang menggantikan watak, sementara skrip dan bahasa masih mendendangkan deru kolonialisme?
Di sinilah projek Fanon memberikan makna yang besar. Fanon dalam The Wretched of the Earth menegaskan bahawa dekolonisasi tidak boleh berhenti pada tahap politik sahaja tetapi ia mesti menyentuh ranah budaya, pengetahuan dan juga cara berfikir.
Begitu juga Robert Young melihat usaha ini sebagai satu bentuk dekonstruksi Barat iaitu langkah yang bukan hanya menolak naratif kolonial tetapi juga menggugat asas epistemologi yang menopangnya. Kemudian selepas itu muncul lagi lebih ramai generasi pemikir yang membawa paradigma yang lebih ragam. Edward Said, Ranajit Guha, Homi Bhabha, Gayatri Spivak yang telah membawa projek nyahjajah ini ke medan wacana yang lebih rumit seperti bahasa, representasi dan kuasa.
Edward Said membongkar bagaimana imej tentang ‘timur’ dicipta oleh Barat untuk mengabsahkan penjajahan. Ranajit Guha pula cuba menulis semula sejarah India dari perspektif massa, bukan elit. Semuanya menunjukkan bahawa nyahjajah adalah sebuah proses yang berterusan, sesuatu yang tidak selesai hanya kerana laungan “Merdeka!” itu sudah dikumandangkan.
Namun hakikatnya, kolonialisme terus hidup dalam naratif besar yang terus membentuk kerangka pemikiran kita. “They believe the work has to go on, particularly in the realm of culture and knowledge, and within the meta-narratives of nationalism, colonialism, capitalism, and socialism, which are all concepts emanating from the West.”3 Di sini muncul dilemanya. Walaupun pemikir pascakolonial kritis terhadap kolonialisme, mereka sendiri masih hidup dalam jagat kerangka teori Barat. Maka ia menimbulkan persoalan yang lain, apakah projek nyahjajah ini boleh dilakukan sepenuhnya dari luar Barat, atau kita tetap terperangkap dan hanya menggugat Barat dari kolam yang sama?
Cheah kemudiannya membawa kita kepada cabaran pascamodenisme. Jean-Francois Lyotard menyebut pascamodenisme sebagai ketidakpercayaan terhadap metanaratif. Jacques Derrida pula menyebut konsep dekonstruksi mengajar kita membaca teks dengan lebih curiga, mempersoalkan siapa yang bercakap dan sudut pandang apa yang diambil. Hayden White lebih keras, katanya sejarah sendiri hanyalah fiksyen, ia tidak pernah memberi kita realiti yang tuntas.
Kini telah wujud pertentangan. Pada satu sisi, nyahjajah menuntut sebuah kebenaran yang dikambus oleh kolonialisme; di sisi lain pula, pascamodenisme menafikan kewujudan kebenaran itu sendiri.
Apa yang menarik, Cheah juga bercakap melalui pengalaman peribadinya. Dalam kajiannya tentang feudalisme Melayu, juga kajiannya tentang The Peasant Robbers of Kedah, beliau dikritik kerana dianggap gagal menyahjajah historiografi kerana masih bergantung pada rekod kolonial. Sedangkan sumber lisan bagi Cheah terlalu kabur dan bercanggah.
“I, therefore, had to fall back on the colonial records—the State Council minutes, the reward notices for the capture of the outlaws, the police reports detailing the outlaws’ activities—to prove their existence. Most of the oral accounts blurred the dates, and the details were either exaggerated or contradictory.”4
Justeru, adakah menyahjajah sejarah bermakna kita harus menolak semua sumber kolonial, walaupun ia mungkin satu-satunya jejak yang ada? Atau adakah ia bermakna kita mesti mengajukan soalan baru terhadap sumber itu, sekalipun ia lahir daripada kerangka kolonial? Kita dapat melihat kejujuran Cheah dalam penggunaannya terhadap sumber kolonial, tetapi pada masa yang sama kita juga harus sedar bahawa cara apa yang kita pertanyakan dan tafsirkan pada satu-satu sumber itulah menjadi medan sebenar dalam projek dekolonialisasi.
Pada akhirnya kata Cheah, cabaran utama bukanlah sekadar soal sumber, tetapi juga persoalan dan konsep yang kita bawa kepada sumber itu. “Increasingly it may take the form of deconstructionist post-modernist history, which is a new, exciting ‘worldly, wordy language game’ which historians can learn to play.”5 Di sinilah pendekatan dekonstruksionis pascamoden boleh menjadi alat yang berguna. Ia mengajar sejarawan untuk memeriksa teks dengan lebih teliti, mencari yang tersirat di balik yang tersurat, membaca makna dalam perubahan bahasa yang halus. Apa yang dikatakan sebagai ‘permainan bahasa’ itu mungkin yang akan membawa kepada penemuan makna yang lebih kompleks dan nuansa yang tidak dapat dilihat melalui kaedah historiografi tradisional.
Membaca makalah ini menginsafi kita akan erti kemerdekaan. 68 tahun kita merayakan pembebasan, hakikatnya di pundak kita yang merdeka itu masih menanggung beban penjajahan. Projek menyahjajah sejarah, juga pengetahuan, akan terus bergulir dan bergeser. Ia bukanlah tentang satu puncak yang harus kita tawan, tetapi ia adalah sebuah advancer yang penuh kegelisahan dan pertarungan.
Mari kita tanyakan, apakah kita masih punya harapan? Hanya kita yang mempunyai jawapan. Kita masih saja boleh melangkah ke hadapan, menulis, bercakap dan berfikir, namun apakah kita punya keberanian dan kesedaran—yang jujur pastinya—untuk kita terus mencari makna tanpa henti, dengan penuh keinsafan, membebaskan pengetahuan dan memerdekakannya dalam erti kata yang sebenarnya.
Footnote
- Cheah Boon Kheng. 1994 “Decolonising History: The Post-Modernist Challenge.” Dalam Asian Studies Association of Australia Biennial Confrence, 13 – 16 July 1994, Murdoch University, Perth Australia. ↩︎
- Cheah Boon Kheng. “Decolonising History,” 1. ↩︎
- Cheah Boon Kheng. “Decolonising History,” 3. ↩︎
- Cheah Boon Kheng. “Decolonising History,” 17-18. ↩︎
- Cheah Boon Kheng. “Decolonising History,” 21. ↩︎